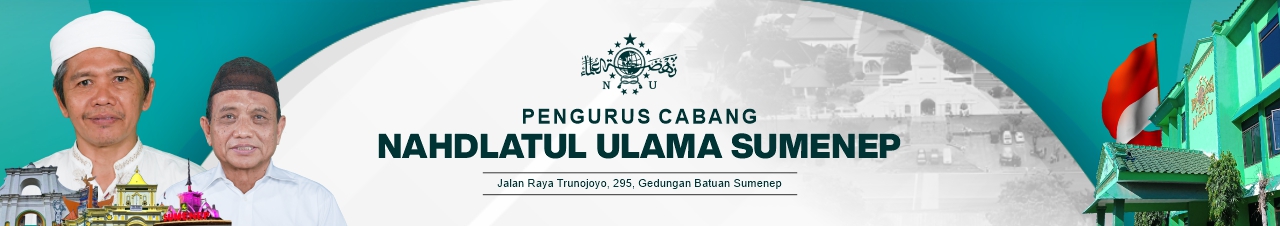Oleh: Ahmad Herzi
Dalam semesta One Piece, Eiichiro Oda membangun dunia fiksi yang penuh warna, tapi juga sarat pesan sosial. Di balik petualangan bajak laut, ia menyelipkan kisah tentang kesewenang-wenangan kekuasaan, manipulasi sejarah, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan akibat kerakusan elit. Dunia itu mungkin rekaan, tapi atmosfernya terasa begitu nyata bagi siapa pun yang hidup di negeri seperti Indonesia hari ini.
Pemerintah Dunia dalam One Piece digambarkan sebagai kekuatan global yang tidak hanya menjalankan politik dan militer, tapi juga mengendalikan narasi sejarah dan membentuk opini publik. Mereka menentukan siapa pahlawan dan siapa kriminal, dan sering kali yang memperjuangkan kebenaran justru dicap sebagai ancaman.
Di Indonesia, kita mengenal bentuk yang serupa: kekuasaan yang terlalu sentral, kritik yang disikapi dengan defensif, dan hukum yang terasa bekerja hanya untuk mereka yang punya akses dan kuasa. Skandal korupsi silih berganti, namun hukuman berat sering hanya menyentuh rakyat kecil.
Laut dalam One Piece adalah simbol kebebasan, namun di banyak pulau, lautan rusak akibat perang, percobaan senjata, dan proyek-proyek kekuasaan. Pulau Punk Hazard, misalnya, rusak total karena eksperimen senjata kimia dan pertarungan antaradmiral. Lautnya menjadi tidak ramah bagi makhluk hidup.
Kondisi ini mengingatkan pada perairan Indonesia seperti Teluk Jakarta, Teluk Balikpapan, atau Teluk Kendari—yang tercemar berat akibat limbah industri, tumpahan minyak, atau aktivitas tambang nikel. Di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, banyak nelayan kecil mengeluh hasil tangkapan merosot drastis. Laut bukan lagi sumber penghidupan, melainkan korban pembangunan yang tidak berpihak pada ekosistem.
Sementara itu, hutan-hutan di One Piece juga tidak luput dari kehancuran. Pulau Ohara, yang dulunya hijau dan damai, dimusnahkan oleh Pemerintah Dunia melalui operasi militer besar (Buster Call), hanya karena para ilmuwannya mencoba menggali sejarah yang dilarang.
Gambaran ini terasa ketika melihat deforestasi yang masif di Papua dan Kalimantan, di mana masyarakat adat sering diusir dari tanah leluhurnya karena menolak proyek industri. Hutan-hutan yang menjadi sumber pengetahuan, spiritualitas, dan pangan dirampas atas nama investasi.
Pulau Wano—khususnya daerah ibu kota lama dan Kota Ebisu—dalam One Piece juga mencerminkan bagaimana industrialisasi yang dipaksakan dapat menghancurkan alam dan manusia. Sungai-sungai tercemar oleh limbah pabrik senjata milik Kaido, menyebabkan penyakit dan kemiskinan.
Ini mencerminkan dampak nyata dari proyek smelter nikel di Sulawesi Tengah dan Tenggara, atau pertambangan emas di Kalimantan dan Sumbawa, yang sering kali menyisakan kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat.
Dressrosa, pulau lain dalam cerita, memberikan pelajaran soal bagaimana tirani bisa dibungkus dengan propaganda. Doflamingo, penguasanya, membangun citra sebagai pemimpin baik hati, padahal ia mengendalikan rakyat dengan ketakutan dan ilusi. Situasi ini tidak asing dalam realita politik kita: pembangunan yang diklaim membawa kesejahteraan justru meninggalkan ketimpangan, penggusuran, dan polarisasi sosial.
Namun satu hal yang selalu hidup di dunia One Piece adalah harapan. Dari pulau ke pulau, selalu ada kelompok rakyat yang berani bersuara, yang tak ingin terus tunduk pada sistem yang menindas.
Di dunia nyata pun, perlawanan datang dari masyarakat sipil: nelayan yang menolak reklamasi, masyarakat adat yang menjaga hutan, mahasiswa yang menyuarakan keadilan, dan aktivis lingkungan yang terus menyuarakan bahaya krisis iklim. Merekalah wajah-wajah keberanian yang tetap menyala di tengah gelapnya birokrasi dan politik transaksional.
Kisah One Piece menunjukkan bahwa dunia yang adil tidak bisa dicapai hanya dengan menunggu. Ia perlu diperjuangkan, bahkan jika itu berarti menghadapi kekuasaan yang besar dan sistem yang mapan. Luffy bukan pahlawan yang sempurna, tapi keberanian dan komitmennya pada kebebasan menjadikannya simbol harapan. Ia berteriak:
“Aku akan menjadi Raja Bajak Laut!”
Bukan karena ingin menguasai dunia, tapi karena ingin menjadi orang yang paling bebas di dunia yang penuh belenggu.
Dan seperti kata Nico Robin, seorang yang diburu karena mencari kebenaran sejarah:
“Aku ingin hidup. Aku ingin melihat dunia berubah.”
Fiksi bisa memberi kita jarak untuk melihat kenyataan secara lebih jernih. Mungkin inilah saatnya kita bertanya:
Mengapa dunia yang kita anggap sebagai dongeng, justru terasa lebih jujur dari kenyataan?
Belakangan ini, aksi pengibaran bendera Roger (Jolly Roger) pada peringatan HUT RI ke-80 tengah viral. Bagi sebagian rakyat kecil, bendera itu menjadi simbol perlawanan—sekaligus ekspresi kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi sosial yang mereka alami.
Sayangnya, pemerintah meresponsnya secara berlebihan, seolah-olah itu sebuah ancaman serius. Padahal, bisa jadi ini hanyalah bentuk ekspresi sosial, bukan tindakan makar.
Padahal Gus Dur pernah berkata “Bintang Kejora boleh dikibarkan sebagai simbol identitas budaya, bukan sebagai lambang kemerdekaan.”
“Bendera, bahkan yang bergambar tengkorak, bukanlah ancaman bila kita mampu membaca maknanya. Dalam pandangan Gus Dur, simbol adalah ekspresi budaya—bukan selalu pertanda makar.”
Mengibarkan bendera Jolly Roger hari ini bukan sekadar candaan fandom atau euforia pop culture. Di balik kain bergambar tengkorak itu, tersembunyi isyarat: kekecewaan yang pelan-pelan berubah jadi perlawanan simbolik terhadap negara yang tak lagi didengar, tapi justru terus mendengar dirinya sendiri.
Dan seperti kata Luffy, ‘Aku hanya ingin menjadi orang paling bebas di lautan.’
Barangkali, itulah suara diam anak-anak bangsa hari ini—mereka tak hendak memberontak, mereka hanya ingin merdeka mengekspresikan diri di negeri yang katanya telah lama merdeka.”