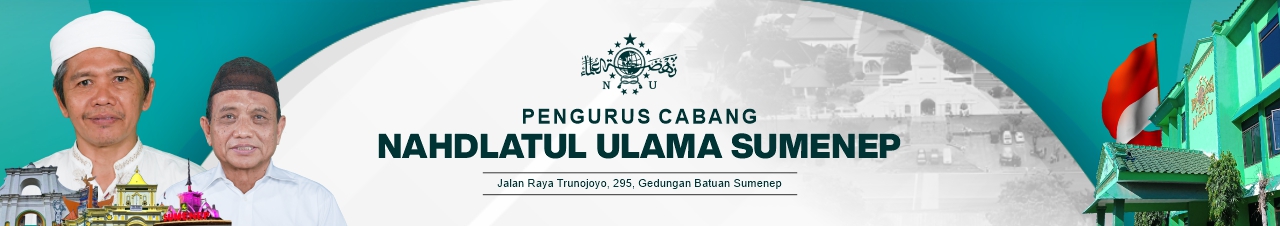Oleh: A. Warits Rovi *)
Saat anak-anak seusianya bisa menulis, membaca, dan menghafal nama-nama nabi dan malaikat beserta tugas-tugasnya, Ipang hanya tahu dari hasil menguping bahwa huruf yang lurus itu bernama Alif dan yang seperti sampan bertitik satu di bawahnya itu adalah Ba’. Itulah sebabnya setiap kali hendak pergi mengemis, ia tak lupa menyambangi jendela surau Kiai Amir untuk sekadar mendengar apa yang diajarkan Kiai Amir kepada santri-santrinya. Bentuk huruf yang ia dengar itu sesekali ia coba tulis dengan jari telunjuknya pada kaca jendela surau yang sedikit berdebu. Lantas ia tersenyum meski tak melihat huruf yang ia tulis itu.
Lahir sebagai tunanetra, membuat Ipang belajar mencari jalan terang di balik kegelapan yang abadi dengan bantuan sebatang tongkat. Pagi hari, saat anak-anak seusianya pergi ke sekolah dengan cakap-canda-tawa yang ceria, ia hanya bisa berpapasan, menghidu tubuh mereka yang wangi, mendengar obrolan mereka yang bahagia, seraya mencoba menerka beberapa kata yang diperbincangkan mereka seperti pizza, game, sepeda baru, tamasya, dan beberapa hal lain yang bagi Ipang tidak pernah ia temui dalam hidupnya. Dan selebihnya, tak jarang ia menerima ejekan dari anak-anak itu dengan sebutan yang menyakitkan. Ipang mengelus dada, di dalamnya seperti dipenuhi sayatan belati. Sedang kedua matanya yang tertutup rapat mengalirkan butiran bening.
Mulki, seorang bos anak jalanan mengambil Ipang dari orangtuanya secara paksa ketika ia berumur tujuh tahun lantaran kedua orang tuanya tak bisa membayar hutang kepada Mulki. Sejak saat itu, ia disuruh mengemis atau kadang memulung sampah. Jika sudah menyetor hasil mengemis atau hasil memulung sampah, barulah Mulki memberinya nasi. Tapi jika ia pulang dengan tangan hampa atau dengan perolehan yang sedikit, Mulki akan memarahi bahkan kadang memukulnya hingga menangis, dan upahnya cuma sebungkus kerupuk yang harus dimakan dengan tiga buah cabai pedas tanpa sisa.
Peristiwa demi peristiwa yang mencambuk dirinya nyaris membuat Ipang putus asa. Beberapa kali ia berpikir untuk mengkahiri hidupnya dengan cara yang lembut, tapi ia teringat Kiai Amir dan seseorang bernama Nabi Muhammad yang sering ia ceritakan kepada santrinya. Jika ingat itu, ia akan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, setidaknya menunda dulu hingga tahu huruf-huruf hijaiyah itu lebih banyak dan tentu setelah bertemu Nabi Muhammad.
#
Pagi itu Ipang menjinjit dan mengarahkan cuping telinganya ke dalam ruangan surau Kiai Amir melalui pojok jendela yang kusennya sedikit berdebu. Debu-debu itu menempel pada lengannya yang kurus, tapi ia tak hirau, pikirannya lebih fokus mendengar suara datar Kiai Amir yang kembali bercerita Nabi Muhammad kepada santri-santrinya. Ipang sangat bahagia, sebab cerita perihal Nabi Muhammad yang ia tunggu, baru dilanjutkan pagi itu setelah sekitar dua minggu Kiai Amir tak menceritakannya saat mengajar.
Umurnya yang masih tujuh tahun dan tidak bersekolah TK membuatnya tidak tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad yang diceritakan Kiai Amir itu. Dari cerita Kiai Amir yang suaranya sesekali disela silir angin, ia hanya bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat baik, ramah, jujur, dan rendah hati. Itulah yang membuat ia betah berdiri di jendela, tak peduli lengannya diparam debu dan kakinya yang menjinjit sudah mulai pegal.
Beberapa menit kemudian, Kiai Amir menyebut Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, ia mengangguk pelan karena tahu bahwa Nabi Muhammad itu rasul, tapi ia tidak tahu arti kata rasul. Ia semakin merapikan posisi tubuhnya dengan kedua lengan terbentang di kusen dan dagunya ditopangkan supaya lebih nayaman mendengar cerita Kiai Amir.
Karena tidak bisa melihat, ia tak sadar bahwa keberadaannya yang nongol di jendela dilihat oleh Kiai Amir dan santri-santrinya dari dalam surau. Sebagian santri Kiai Amir malah ada yang merasa kehadirannya di kusen jendela itu mirip Upin yang menampakkan kepala plontosnya di kotak telivisi, membuat mereka terhibur dan merasa lucu.
Berkali-kali Ipang membetulkan arah cuping telinganya. Juga berkali-kali mengubah posisi jinjitnya agar tak pegal. Semuanya untuk mendengar cerita tentang Nabi Muhammad dari Kiai Amir, yang membuat hatinya serasa menemukan sebuah keindahan, dan ia baru sadar bahwa keindahan tak semata bisa didapat dari mata. Pagi itu ia merasa keindahan datang melalui telinganya. Sesekali terlintas sebuah keinginan di benaknya untuk bertemu Nabi Muhammad.
“Semoga suatu saat aku bisa bertemu Nabi Muhammad. Dia pasti orang yang lembut. Tidak seperti Om Mulki yang kasar dan bisanya cuma menyuruhku mencari sampah untuk ia jual. Satu karung hanya diupah lima ratus rupiah. Jika tidak sesak, ia memarahiku dan bahkan memukulku. Atau ia menyuruhku mengemis di depan supermarket seharian, yang membuatku kadang diejek dan kadang dimarahi oleh orang-orang, atau kadang diusir oleh Pak Satpol PP”.
Sejenak ia mengenang kejadian pahit yang sering menimpa dirinya. Ada butiran dingin bergulir dari sudut kedua matanya yang rapat tertutup. Jari-jemarinya yang kurus berjuntai kuku hitam berdaki sesekali menyeka air mata itu. Ia sedikit gemetar dan terisak. Kadang kala, tangan kanannya harus memegang tongkat yang ia bawa untuk mengurangi beban tubuhnya yang sedang berdiri.
“Ingin sekali aku bertemu Nabi Muhammad. Aku ingin minta doa pada beliau supaya aku bisa bertemu dengan kedua orangtuaku, bahkan jika bisa, aku ingin beliau membuka mataku agar bisa melihat. Aku ingin…, eh tapi beliau sekarang di mana ya?” ia menggaruk kepala dan mengernyitkan dahi.
“Hei hei! Kamu kok berdiri di sini? Kapan karung ini akan berisi?” seketika Mulki menarik lengan Ipang dengan kasar dari belakang, seraya menaruh sebuah karung yang sedari tadi ada di tanah ke dalam genggamannya. Ia lupa bahwa pagi itu harus memulung sampah demi bisa mendapatkan sepeser uang dari Mulki.
Ia melangkahkan kaki dengan gerak yang lirih. Di dadanya ada keinginan untuk terus mendengar cerita Kiai Amir sampai selesai. Pikirannya masih diliputi rasa penasaran kepada Nabi Muhammad. Pada jarak yang tak begitu jauh, ia menghentikan langkah, ada keinginan untuk kembali ke kusen jendela, setidaknya ingin bertanya di mana rumah Nabi Muhammad.
“Hei! Kok masih berhenti. Ayo pergi!. Ini sudah siang. Apa kamu tak ingin makan?”
Suara Mulki membuatnya terperanjat. Ada getar perih di dadanya seiring cahaya matahari menimpa kulit tubuhnya yang kering.
#
Pagi itu Ipang berangkat enam menit sesudah subuh ketika jalanan masih gelap. Ia berpikir, gelap dan terang sama saja, keduanya tetap berwarna hitam bagi seorang tunanetra seperti dirinya. Saat pamit, Mulki masih lelap berselimut sarung. Ia menjawab seperti orang teler. Ipang rela menapak jalan yang lengang, gelap, dan dingin demi memenuhi keinginannya untuk bertemu Kiai Amir sebelum ia mengajar kitab di suraunya. Maksudnya cuma satu; untuk menanyakan siapa dan di mana Nabi Muhammad.
Setelah menunggu sekitar 21 menit sambil duduk menahan dingin di bawah sebatang pohon kurma, akhirnya Kiai Amir melintas di jalan kecil yang menghubungkan rumah dan suraunya. Suara batuk Kiai Amir sudah Ipang hafal, sehinga ia langsung bersalaman dengan mencium punggung tangan Kiai Amir. Dengan polos, ia mengaku bahwa hampir setiap pagi dirinya diam-diam mengikuti pengajian kitab yang diajarkan Kiai Amir di balik jendela surau. Cerita Nabi Muhammadlah yang membuat dirinya selalu ingin mendekat ke jendela untuk mendengarnya hingga tuntas. Kiai Amir tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ia pun langsung bertanya perihal Nabi Muhammad. Senyum Kiai Amir kian lebar, menampakkan baris gigi putihnya seperti nyaris hendak tertawa. Ia merasa lucu dengan pertanyaan Ipang. Ia menepuk-nepuk bahu Ipang.
“Nabi Muhammad itu nabi kita semua. Beliau utusan Allah. Apa kamu pernah baca kalimat syahadat?” tanya Kiai Amir sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Ipang yang tirus.
“Kalimat syahadat? Apa itu, Kiai?”
“Kalimat syahadat itu rukun Islam yang pertama, sebuah pernyataan atau kesaksian bahwa Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad adalah utusanNya.”
“Kalau Allah adalah Tuhan saya sudah tahu, tapi kalau Nabi Muhammad utusan saya baru tahu.”
“Nah! Ayo sekarang kamu baca kalimat syahadat, ikuti saya ya.”
“Baik, Kiai.”
Kiai Amir membaca kalimat syahadat dengan pengejaan yang jelas dan pelan. Ia mengulanginya dua kali. Ipang tersenyum. Sayatan luka oleh ratapan nasib di dalam dadanya sejenak lenyap oleh ketenangan, kedamaian, dan kesejukan saat mendengar kalimat itu. Kemudian Kiai Amir menyuruh Ipang membacanya. Ipang mencoba membacanya pelan dan mengulanginya beberapa kali hingga fasih. Kiai Amir kembali menepuk-nepuk bahu Ipang dengan lembut seraya memuji kefasihannya.
“Terima kasih, Kiai. Ternyata selain saya punya Tuhan, saya juga punya utusan bernama Nabi Muhammad yang sering Kiai ceritakan saat mengajar itu. Kini jiwa saya tenang karena di balik nasib ini ada dua kekuatan yang bisa kujadikan tempat mengadu. Dengan kalimat syahadaat tadi, serasa saya sudah bisa melihat dunia meski dalam keadaan buta. O, Ya. Rumah Nabi Muhammad di mana, Kiai? Saya ingin bertemu beliau.”
Kiai Amir masih tersenyum, kali ini sambil meneteskan air mata haru dari kedua sudut matanya. Telapak tangan yang semula bertumpu di bahu Ipang beralih mengelus lembut rambut bocah itu yang kusut dan kemerahan. Perlahan Kiai Amir memeluk tubuh Ipang sambil terus terisak.
“Beliau sudah wafat, Nak. Beliau hidup sekitar 1400 tahun yang lalu. Tapi meski wafat, beliau tetap akan datang kepadamu, syaratnya cuma dua; rajin baca selawat dan tirulah sikap beliau.”
“Selawat? Apalagi itu, Kiai?”
Kiai Amir melepas pelukannya. Perlahan ia jongkok hingga tingginya setara dengan Ipang. Kedua tangannya bertumpu di kedua bahu Ipang.
“Selawat itu doa kita untuk Nabi Muhammad. Selawat banyak macamnya. Ada selawat Nariyah, selawat Syifa’, selawat Asyghil, dan lainnya. Tapi yang paling simpel bacaanya begini, allahumma sholli ‘ala Muhammad.”
Ipang mengangguk dan meminta Kiai Amir mengulanginya dua kali lagi. Lalu ia menirunya pelan, mengulanginya lagi, dan lagi hingga ia fasih.
“Bacaan selawat yang dibaca pada sewadah air, maka airnya akan barokah, bisa menyembuhkan banyak penyakit, baik penyakit raga maupun penyakit jiwa. Dan yang paling penting, siapa yang rajin baca selawat, kelak di akhirat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad,” imbuh Kiai Amir.
“O, begitu, Kiai. Sungguh luar biasa manfaat selawat ya, Kiai. Terima kasih atas kabarnya, Kiai.”
Kiai Amir tersenyum, mengamati wajah Ipang yang seperti menyimpan kecintaan kepada Sang Nabi di balik kedua matanya yang tak bisa melihat.
“Matahari sudah terbit, saya harus ke surau. Bila kamu berkenan, mari mengaji ke sana,” ajak Kiai Amir.
Ipang menunduk, perlahan tersenyum.
“Saya harus mencari sampah, Kiai. Mmmm, Jika kiai tidak keberatan, besok pagi dan seterusnya, apabila memungkinkan saya akan datang pagi-pagi sekali ke sini dan akan bertanya tentang kisah Nabi Muhammad beserta sikap-sikap beliau yang patut kita teladani.”
“Oh, iya, bisa. Datanglah ke sini sepagi hari ini, temui aku di beranda rumah sebelum aku mengajar di surau, sebisa mungkin aku akan bercerita kepadamu perihal Nabi Muhammad meski dengan sedikit demi sedikit.”
“Terima kasih, Kiai. Bocah buta dan malang seperti saya ini sangat sulit untuk bisa belajar di suarau apalagi di sekolah. Saya berniat menjadikan cerita Nabi Muhammad sebagai sekolah satu-satunya tempat saya mendapat ilmu.”
“Hebat kamu!. Nabi Muhammad beserta sikapnya memang universitas kehidupan, tempat yang tepat bagi umatnya untuk belajar.”
Kiai Amir tertawa kecil, lalu bergegas menuju surau, Ipang menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan pelan. Merasa ada ketenangan dalam dadanya. Sepasang matanya yang selama ini diliputi kegelapan, serasa didatangi cahaya.
Ia menimbang keadaan, meski sebelumnya sudah bilang ingin segera mencari sampah kepada Kiai Amir, tapi terbersit keinginan untuk sejenak menguping pengajian Kiai Amir melalui jendela surau seperti hari-hari sebelumnya. Ia membentangkan lengannya di udara dan beberapa kali digerak-gerakkan untuk diletakkan pada posisi yang tersorot cahaya matahari, cara itu biasa Ipang lakukan untuk membaca pergeseran waktu, apakah masih pagi atau tidak.
Kaki Ipang mulai diarahkan ke surau, tepatnya pada jendela tempat biasa ia menguping Kiai Amir. Baru dua kali melangkah, ia dikejutkan oleh sebuah jeweran dari belakang.
“Hei, hei! Masih mau ke mana? Ini saatnya kamu pergi mencari sampah dan mengemis wahai bocah buta,” suara bentakan Mulki membuat Ipang gemetar dan diam tanpa kata.
“Ayo cepat pergi!. Jangan pulang sebelum membawa setoran yang banyak.”
“Pyarrrrr!!”
Seutas rotan yang sejak tadi dipegang Mulki, menyisakan garis merah di betis Ipang.
#
Mulki duduk berselonjor di lincak kayu sembari menyalakan rokok diselingi minuman dan camilan. Keadaan sedikit senyap, karena di kamar sebelah, rekan-rekan Ipang, bocah-bocah pemulung dan pengemis lainnya anak buah Mulki itu sudah tidur. Mulki terus memarahi Ipang yang duduk bergeming di lantai kotor sambil menggosokkan telunjuknya pada sekumpulan debu, sesekali mengatur gerak telunjuknya itu membentuk haruf Alif atau Ba’, lalu menghapusnya, menulisnya kembali, kemudian purna dihapus saat kedua tangannya menyatu di betisnya yang tengah bersila.
Meski malam semakin larut, sekadar menyisakan sunyi dan geletar angin, Mulki tetap menyaringkan suaranya, ia membentak-bentak Ipang karena perolehan mengemis yang sedikit. Saat batang rokoknya memendek jadi puntung, ia melemparkannya ke wajah Ipang.
Ipang hanya menunduk, seperti telah biasa menerima perlakuan keras yang menyakiti jiwa dan raganya itu. Andai dalam benaknya tidak ingat kepada Nabi Muhammad, ingin segera dirinya bunuh diri. Tapi ketika ingat cerita Kiai Amir, ia merasa malu jika sampai bunuh diri, Nabi Muhammad sejak kecil juga hidup dalam penderitaan, namun ia tegar dan tabah.
Malam itu, setelah Mulki tertidur karena kelelahan sesudah marah-marah. Perlahan Ipang beranjak ke dapur. Mengambil sebotol air. Ia lalu duduk bersila dan membaca selawat di kamar sempitnya yang kumuh, botol itu diabaikan terbuka di depannya. Meski malam semakin larut dan dan dirinya merasa lelah, tapi ia menemukan kenikmatan saat membaca selawat, serasa bibirnya yang bergetar tak ingin mengakhiri bacaan itu, serasa Nabi Muhammad hadir dan mengelus kepala Ipang penuh kasih. Menjelang subuh, ia meraih sebotol air di hadapannya, lalu meneguknya beberapa kali. Ipang merasakan air itu tidak sekadar membawa kesejukan pada raganya, melainkan juga membawa kesejukan pada jiwanya.
Seusai salat subuh, Ipang beranjak ke kamar sebelah, suara dengkur Mulki menyaingi kicau burung kecil yang terdengar dari arah ventilasi. Tangan Ipang meraba barang-barang di sekitar tubuh Mulki dan berhenti saat menyentuh guci keramik berisi air. Ipang tahu, itu air yang biasa diminum Mulki. Ipang merogoh sebotol air miliknya, lekas memutar tutupnya hingga terbuka, kemudian ia tuangkan ke dalam guci keramik dengan hati-hati. Bunyi air itu sebentar membuat Mulki menggeliat sebelum akhirnya mendengkur lagi.
Seperti biasa, Ipang pamit kepada Mulki yang masih tidur, dan Mulki menjawab sekenanya. Pagi itu Ipang melangkahkan kaki dengan perasaan yang lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya, sebab ia merasa punya teman baru berupa sebotol air selawat yang tersimpan di saku bajunya.
#
Ipang meraba batas dingin di dinding botol dan sesekali mengocoknya di dekat telinganya untuk mengetahui volume air yang tersisa. Mulanya, ia mengisi botol itu satu kali setiap hari. Tapi seiring berjalannya waktu, ia sendiri tak menyangka, ternyata banyak yang membutuhkan air itu, hingga akhirnya harus diisi tiga kali sehari. Dan tiga kali pula ia harus duduk bersila membaca selawat pada air itu.
Awalnya, ia sekadar mengoleskan air itu pada kaki tukang parkir yang luka akibat tergencet standar motor di dekat supermarket tempat Ipang mengemis. Si tukang parkir menjulurkan kakinya enteng dengan maksud sekadar mempermainkan Ipang sambil cekikikan. Ipang melingkari luka itu dengan olesan air yang ia teteskan dari botolnya. Tak lama setelahnya, si tukang parkir lantas seperti tak percaya dan ia tercengang begitu mendapati luka di kakinya perlahan mengering dan perihnya hilang seketika. Hanya butuh waktu 4 menit si tukang parkir kembali bekerja seperti biasa tak sedikit pun merasakan sakit di kakinya. Ia pun merasa berhutang budi kepada Ipang, selembar uang 5000-an diselipkan ke saku baju Ipang, tapi Ipang menolak dengan santun.
“Mengapa kamu menolak? Kamu kan pengemis? Ke sini memang untuk mencari uang?” tanya si tukang parkir.
“Saya memang pengemis yang butuh uang, tapi saya tak ingin menukar air itu dengan uang. Sebab saya malu kepada Nabi Muhammad bila air yang dibacakan selawat itu ditukar dengan uang.”
“Aku tak bermaksud untuk menghargai airmu tadi. Ini sekadar pemberianku kepadamu layaknya orang-orang melempar uang ke wadah di depanmu itu.”
“Saya baru saja membantu bapak, dan seketika bapak mau memberi uang kepada saya. Itu memicu ketidaknyamanan di antara kita, hehe.”
“Hehe.”
Keduanya tertawa. Ipang memasukkan botol ke dalam saku bajunya. Sedang si tukang parkir diam-diam menaruh uang itu ke wadah karet yang ada di depan Ipang. Sejak saat itulah kabar keberkahan air itu tersebar setelah si tukang parkir bercerita kepada beberapa orang.
Setiap hari banyak orang yang mendatangi Ipang untuk minta air selawat. Ada yang hendak digunakan untuk mengobati penyakit, untuk menyembuhkan orang gila, penglaris dagangan, penjinak hewan liar, pemacu sapi karapan, hingga untuk menambah anggun wajah orang yang akan menikah.
Di depan supermarket, orang-orang mengerumuninya, minta air dan diam-diam menaruh uang di wadah karet tempat uang dari hasil mengemis. Ia kini lebih pas disebut tabib dengan pasien yang membludak. Uang berhamburan di sekitarnya hanya dalam kurun waktu satu jam. Wadah karet di depannya selalu tak muat dengan uang yang banyak itu. Di sela waktu sepi, ketika orang-orang di sekelilingnya tinggal sedikit, kadang terlintas kalimat tanya di benak Ipang
“Apakah engkau berkenan dengan semua ini, Nabiku? Kami sebenarnya bermaksud memberi air ini cuma-cuma, tapi mereka masih meninggalkan uang di sini. Uang ini tidak akan saya setor seluruhnya kepada Om Mulki. Saya akan menyisakannya untuk kaum duafa.”
Ia menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskannya perlahan, seraya ia raba batas dinding botol itu untuk memastikan keberadaan air di dalamnya. Lalu ia membentangkan lengannya di udara, tak ada sorot matahari yang menyentuhnya selain rasa dingin yang sedikit menusuk. Ipang menyimpulkan, hari sudah senja, saatnya ia pulang.
#
Kabar Ipang yang sering mengobati orang-orang di depan supermarket sampai juga ke telinga Mulki. Suatu waktu ia menanyakan hal itu kepada Ipang. Yang membuat Ipang kaget justru bukan karena kabar dirinya didengar Mulki, tapi ia kaget pada sikap Mulki yang perlahan berubah jadi lembut. Saat bertanya tentang kebenaran kabar Ipang yang menjadi tabib itu, intonasi suara Mulki teramat datar dengan tempo yang agak lambat sehingga terdengar sopan, mirip seorang guru yang begitu wibawa berbicara kepada muridnya. Ia sama sekali tak menampakkan respon marah di wajahnya, malah bibirnya yang hitam ada kalanya bertaut senyum.
Sikap Mulki yang demikian itu membuat Ipang tak tega bila harus berbohong, ia pun berterus terang, bahwa sejak sebulan yang lalu, dirinya tidak hanya mengemis, tapi juga mengobati orang yang sakit dengan sebotol air selawat. Ipang pun berterus terang jika perolehan uangnya—selain disetor kepada Mulki—sebagain dibagi kepada kaum duafa.
Mulki tersenyum mendengar kabar itu, ia tak protes apa-apa, malah menyarankan Ipang untuk rajin membantu orang meski tak mendapat imbalan sekalipun. Ipang mengangguk walau di benaknya sedikit ragu pada sikap Mulki yang seketika berubah.
“Ada apa kok Om Mulki sikapnya berubah dingin?” tanyanya dalam hati.
#
Petang itu, ketika Ipang baru saja selesai salat magrib, Mulki mendatangi kamar Ipang dan duduk di sebelahnya, pada sisa hamparan sajadah yang menyentuh tembok. Kedatangan Mulki yang tiba-tiba, membuat Ipang sedikit panik karena ia tak sempat mengamankan sebotol air selawat yang ditaruh didepannya. Tapi Mulki tak beraksi apa-apa, Ipang hanya mendengar napas Mulki yang teratur pertanda ia tetap duduk tenang dan tidak ada tanda-tanda untuk marah. Ipang terus membaca selawat dengan pelalafalan yang lirih. Kesnyuian setelah magrib seolah bentang laut tenang untuk melarung sampan rindunya kepada Nabi Muhammad.
“Pang,” tangan Mulki menyentuh pelan bahu Ipang.
“Iya, Om.”
“Hari demi hari rasanya aku tidak semakin nyaman hidup seperti ini. Usia terus berkurang dan sudah pasti mendekati mati,” Mulki menghentikan pembicaraannya. Ipang masih terdiam, tak berani merespon karena belum tahu ke mana arah pembicaraan Mulki. Keduanya diterpa senyap.
“Aku ingin kamu kukembalikan kepada orang tuamu, begitu juga anak buahku yang lain, semua akan kukembalikan kepada orang tuanya,” ungkap Mulki sembari memijat bahu Ipang pelan-pelan. Kata-kata Mulki membuat Ipang terperanjat antara bahagia dan tak percaya.
“Lalu Om Mulki akan mau ke mana?”
“Aku juga rindu keluarga di kampung. Aku ingin tinggal bersama anak dan istri, serta ingin hidup wajar dengan bekerja sebagaimana mestinya seperti dulu.”
Suara Mulki agak bergetar seperti menahan tangis. Ipang hanya membisu, bibirnya rapat terkatup, kecuali hanya jemari tangan kanannya yang meremas-remas botol di depannya perlahan hingga menimbulkan bunyi yang berkriyek-kriyek.
“Itu air apa yang ada di depanmu, Pang?” tanya Mulki seketika, membuat Ipang terkejut dan segera menghentikan gerakan jemarinya.
“Oh, ini. Ini, ini air anu, Om. Air selawat yang biasa saya pakai untuk mengobati orang-orang.”
“O, jadi itu air selawat yang kauceritakan itu, Kok bisa disebut air selawat?”
“Karena air ini saya bacakan selawat dengan rutin, Om.”
Sejenak Mulki terdiam mengamati air itu.
“Apa bisa menenangkan jiwa?” tanya Mulki kemudian.
“Insya Allah bisa, Om.”
“Boleh aku minta?”
“Boleh. Ayo ini, Om,” sahut Ipang seraya meraba-raba, sebelum akhirnya ia meraih sebuah gelas dan menuangkan air itu ke dalamnya. Kemudian Mulki meminum air dalam gelas itu. Ipang menghikmati setiap suara tegukan Mulki seolah bisikan lembut dari kanjeng Nabi Muhammad. Ia juga teringat pada apa yang ia lakukan setiap subuh, sesaat sebelum pergi mengemis; senantiasa tak melewatkan kesempatan untuk mericikkan air selawat itu ke dalam air minum Mulki dalam guci keramik. Ipang yakin bahwa sikap lembut Mulki kemungkinan besar karena pengaruh dari air selawat.
“Nikmat sekali. Lain kali, sisakan lagi buatku ya!”
“Insya Allah, Om.”
Mulki beranjak pergi setelah mengulangi rencananya untuk mengantar Ipang kepada orang tuanya di kampung. Ipang mengangguk sembari membayangkan betapa bahagianya nanti setelah ia bisa mencium punggung tangan kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tak pernah berjumpa.
#
Selesai salat subuh, Ipang mengepak barang-barangnya dalam tiga kardus kecil yang diikat tali rafia. Hari itu adalah hari terakhir bagi dirinya untuk menikmati udara kota itu, sebab keesokan harinya ia akan diantar kembali pada orang tuanya di kampung. Ipang ingin hari terakhir di kota itu menjadi hari yang indah, setidaknya ia harus menyambangi Kiai Amir terlebih dahulu untuk pamit dan berharap ada cerita pemungkas yang paling mengesankan tentang Nabi Muhammad.
Ipang membentangkan lengannya di udara, ada sorot cahaya matahari pagi yang sedikit menyengat. Ia pun bisa menebak jika saat itu sekitaran pukul 06.00. Ia segera bergegas menuju surau Kiai Amir dengan bantuan sebatang tongkat yang biasa menemani dirinya mengenal berbagai medan jalan. Sepanjang perjalanan ke surau Kiai Amir, ia menikmati setiap ketukan tongkat yang menyentuh tanah sebagai ucapan pamit dari seorang tunanetra. Sesekali kedua matanya yang tertutup rapat menetes air mata haru, betapa ia tak pernah menyangka dirinya akan segera kembali kepada orang tuanya dengan cara semudah itu.
Sebentar ia menghentikan langkah. Bersandar sebatang pohon rindang, menghela napas, dan meraba sebotol air selawat di saku bajunya. Ia mulai menduga-duga; mungkin berkah air selawat itu yang jadi penyebab terbentangnya jalan kemudahan untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Ia teringat bagaimana dirinya diam-diam menuangkan sebagian air itu ke dalam air minum Mulki setiap selesai subuh. Barangkali sebab itula hati Mulki yang keras perlahan berubah lembut. Ia juga teringat ketekunan dirinya membaca selawat pada air itu dan meminumnya dengan tekun. Tangannya mengelus botol itu di sakunya.
“Betapa dinginnya air ini, sedingin hatiku, sedingin sikap Nabi Muhammad yang senantiasa bisa melenyapkan setiap hati yang tandus,” gumamnya, perlahan melanjutkan langkah, tingaal dua kali tikungan untuk sampai di rumah Kiai Amir. Ia tak sabar untuk mendengar kisah paling berkesan tentang Nabi Muhammad sebelum dirinya pulang kampung.
Setiba di pekarangan Kiai Amir, ia agak heran mendapati keadaan yang begitu lengang. Di dalam rumah itu seperti tak ada siapa-siapa. Ia mundur beberapa langkah mengubah haluan ke arah surau. Lalu seorang santri mendekatinya.
“Kamu mau ke mana, Dik?”
“Saya ingin bersilaturrahmi pada Kiai Amir.”
“Mohon maaf, Dik. Kemarin sore Kiai tiba-tiba sakit, hari ini beliau ada di rumah sakit.”
“Ha? Beliau sakit dan sekarang ada di rumah sakit?”
“Iya.”
Ipang mematung. Dalam kelam pandangannya ia serasa melihat Kiai Amir mengulur tangan untuk meminta air selawat.
#
Ipang tak pernah menduga, sepasang kakinya kembali bisa menapak halaman rumahnya seperti pagi itu. Meski ia harus menyunggi dan memikul kardus berat sekitar setengah kilometer dari jalan raya menuju rumahnya, tapi terasa tak ada beban sama sekali oleh sebab rasa kebahagiaan yang membuncah. Orang-orang menyapanya dengan nada penuh keceriaan, seolah mereka mendapati kembali sebutir mutiara yang pernah hilang.
Paman dan bibinya berlari memeluknya dengan tangis haru yang dahsyat. Ipang pun tak bisa menahan air mata harunya. Tetangganya berdatangan, menyapa dengan isak tangis haru.
“Mana ayah dan ibu?”
Semua terdiam, termasuk paman dan bibinya, hanya terdengar isak bersahut. Kemudian Ipang menggerakkan tongkat, menuju pintu rumahnya. Saat menyentuh engkol pintu yang sedikit berdebu, ia serasa bersalaman dengan masa lalunya.
“Ayah!!.. Ibu…!!”
Tak ada yang menjawab dari dalam rumah itu, selain silir angin keheningan, juga bayang-bayang masa lalu yang melebur dalam perasaan.
“Ayah! Ibu!” Ipang mengulangi panggilannya, seraya beranjak masuk ke dalam. Kakinya menyandung gumpalan debu, hidungnya menghidu bau sedikit apek. Terdengar lesat tikus lari menghindar. Ipang merasakan adanya tanda-tanda rumah itu telah lama tak dihuni.
“Ayah! Ibu! Ada di mana kalian? Ini anakmu datang untuk kalian,” suara Ipang sedikit serak.
“Ayah dan ibumu..,” pamannya yang sedari tadi mengikuti dari belakang tiba-tiba hendak menjawab, tapi suaranya terputus. Ia menunduk menyeka butir air mata yang tak terasa keluar.
“Ke mana ayah dan ibu, Paman?”
“Me.., me.., mereka……..” Pamannya membisikkan kalimat berikutnya ke telinga Ipang dengan wajah yang murung.
“Ha? Apa betul begitu paman?” seketika Ipang terkejut. Tubuhnya gemetar. Sepasang matanya yang tertutup rapat, kembali menggulirkan butiran dingin.
Ipang menjerit sekuat tenaga sambil terus menangis. Tongkat yang ia genggam terlepas jatuh begitu saja. Tubuhnya lunglai menyatu dengan lantai yang diparam debu. Ada sakit yang begitu menghunjam. Ia berguling-guling. Beberapa orang yang sempat bediri di pintu ikut menangis. Dalam tangis duka yang mencekik itu ia merogoh sebotol air di saku bajunya, lantas duduk dan meneguknya, berharap air itu mampu mengganti air matanya yang keluar.
#
Hari masih pagi. Seperti biasa, Ipang bisa menebaknya setelah lengannya dibentangkan untuk mengetahui keadaan cuaca. Setidaknya sudah ratusan Fatihah yang sudah ia baca di dekat kuburan bernisan hijau yang membujur senyap di bawah pohon kemboja itu. Ipang masih duduk bersila seraya menundukkan wajah seolah menekuri alamrhum yang pernah berjasa bagi dirinya. Ia lalu membaca selawat sambil sesekali meminum air selawat dalam botol yang selalu terselip di saku bajunya.
Menit-menit akhir sebelum pulang, ia meneteskan air selawat itu ke ujung jari telunjuknya. Lalu telunjuk basah itu ia oret pada batu nisan, membentuk dua huruf hijaiyah yang diketahui Ipang dengan menguping; satu huruf tegak seperti cagak dan satunya berupa garis horizonyal yang lengkung di kedua ujungnya mirip sampan dengan sebuah titik di bawahnya. Ia bangga bisa tahu dan menulis huruf Alif dan Ba’ dalam keadaan buta. Ipang tersenyum.
“Siapa orang yang bersemayam dalam kubur itu, Nak?” tiba-tiba suara ibu tua terdengar di belakang Ipang. Ibu dengan tubuh kurus berpakaian lusuh itu berusaha memajukan langkah untuk lebih dekat dengan Ipang. Sepasang matanya jarang berkedip, terpaku menatap wajah Ipang, seolah ia mengenal Ipang, tapi masih diliputi keraguan untuk memanggil namanya.
“Beliau Kiai Amir, Bu. Darinya saya bisa mendengar kisah Nabi Muhamma, bisa membaca selawat, sekaligus bisa menulis dua huruf hijaiyah,” jawab Ipang sembari memasang tutup botol.
“Beararti kamu anak sini juga?” tanya ibu itu sambil mengernyitkan dahi seperti penasaran.
“Tidak, Bu. Saya dari kampung Baliyan. Kemarin datang ke kota ini karena mendengar Kiai Amir sudah wafat, sekalian demi menghibur diri karena di kampung saya tinggal sendirian, ayah dan ibu tidak ada.”
“Ke mana ayah dan ibumu, Nak?”
“Kata paman, ayah sudah meninggal dan ibu pergi mencari saya entah ke mana.”
“Apa? Ibumu mencarimu? Maksudmu bagaimana?”
“Dulu, ketika masih kecil, saya tinggal bersama ayah dan ibu di kampung. Tapi setelah itu aku diambil paksa oleh seseorang karena ayah dan ibu tidak bisa melunasi hutang kepadanya. Selama lima tahun saya hidup bersama orang yang mengambil saya itu, kemudian dia mengembalikan saya ke kampung sebulan yang lalu, tapi sayang, saya tidak bisa bertemu kedua orangtua saya. Ayah meninggal dan ibu mencari saya.”
“Hah, apa kamu bernama Ipang?” telapak tangan ibu itu mengusap rambut Ipang dengan lembut.
“Ibu kok tahu?”
Ibu itu tidak menjawab. Ia langsung memeluk tubuh Ipang dengan erat sambil menangis keras dan mencium pipi Ipang berkali-kali. Ipang bingung, ia hanya terdiam dalam pelukan si ibu, sesekali ia merasakan hangat pelukan itu seperti pernah ia kenal.
“Ibu siapa?”
Ibu itu tidak menjawab. Ia menatap wajah Ipang dengan derai air mata. Bibirnya gemetar seperti tak bisa melontar kata-kata. Kedua telapak tangannya mengelus lembut pipi Ipang.
“A..aku…aku ibumu, Nak!”
Ibu itu kembali memeluk Ipang dengan tangis. Ipang pun tak kuasa melontar kata-kata. Ia dihalau rasa bahagia yang membuncah. Kedua matanya yang buta pelan-pelan meneteskan air mata haru. Ia balas memeluk ibunya dengan erat sebagai labuh suci bersampan-sampan rindu yang berabad mengapung di laut hitam.
Ipang teringat pada sebotol air selawat yang ia pegang. Ia pun ingat Nabi Muhammad. Terlintas di benaknya sebentuk doa, “Semoga kelak di akhirat saya bisa memelukmu wahai baginda nabi, sehangat pelukan ini.”.
“Pasti semua yang terjadi berkah air selawat ini, berkah dari Nabi Muhammad,” gumam Ipang dalam hati.
Masih dalam pelukan haru, perlahan ia mengangkat sebotol air selawat itu persis di belakang bahu kanan ibunya, lurus dengan kedua matanya yang buta. Andai bisa melihat, ingin sekali ia bercermin sebotol air selawat itu untuk melihat bayangan wajahnya saat bahagia bertemu sang ibu.
Rumah FilzaIbel, 10.20
*) A. Warits Rovi, Redaktur Pelaksana pcnusumenep.or.id . Buku cerpennya yang telah terbit “Dukun Carok & Tongkat Kayu” (Basabasi, 2018).